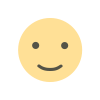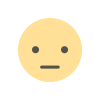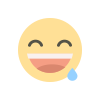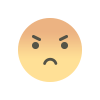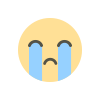Eksil ditawari kembali menjadi warga negara Indonesia - 'Kalau ditawari dwikewarganegaan saya mau'
Sebagian eksil menyambut datar rencana pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk memulihkan kewarganegaraan orang-orang yang terhalang pulang sesudah peristiwa 1965. Mereka tetap menuntut pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dalam tragedi yang memaksa mereka kehilangan status WNI.

- Rohmatin Bonasir
- Wartawan BBC News Indonesia, London

Sumber gambar, Dokumentasi Soegeng Soeyono
Sebagian eksil menyambut datar rencana pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk memulihkan kewarganegaraan orang-orang yang terhalang pulang sesudah peristiwa 1965, sebagian lainnya menaruh harapan tipis dengan catatan.
Rencana pemulihan kewarganegaraan ini dilakukan menyusul pengakuan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965, sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Ketika peristiwa berdarah terjadi, mereka sendiri tidak berada di Indonesia. Sebagian tengah menempuh studi, beberapa lainnya menghadiri acara internasional atau menjalankan tugas diplomatik.
Tiga menteri rencananya akan diutus menemui para eksil di Eropa, sebagian besar berada di Belanda. Sejauh ini belum jelas berapa jumlah korban pelanggaran HAM berat yang ada di luar negeri yang masih hidup. Pemerintah baru akan melakukan verifikasi sesuai instruksi presiden.
Adapun Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan mereka pada Rabu (22/03) di Amsterdam, Belanda, dan di Praha, Republik Ceko pada Sabtu (18/03).
Guna mengetahui sikap dan pandangan eksil terkait pengakuan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa itu dan tawaran pemerintah untuk memulihkan hak korban termasuk memberikan paspor Indonesia, saya menghubungi beberapa eksil di negara-negara Eropa.

Sumber gambar, SEKTRETARIAT KABINET/TWITTER
Sikap dari Praha dan Stockholm
Dari ujung telepon, suaranya terdengar sangat ramah dan bersemangat.
"Sebelumnya saya wanti-wanti ya mbak, umur saya ini akan 84 tahun bulan Juni ini jadi pendengaran saya sudah tidak bagus lagi. Suaranya tolong dikeraskan kalau saya tidak bisa mendengar," pinta penerima telepon sambil tertawa terkekeh-kekeh.
Mungkin berkat sambungan telepon yang bagus atau juga kualitas pendengarannya tidak seburuk yang digambarkan, nyatanya saya tidak sampai perlu meninggikan suara atau mengulang pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaan dasar kepada penerima telepon, Soegeng Soejono, akrab dipanggil Soejono, adalah bagaimana tanggapannya terhadap rencana Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tragedi gerakan 30 September atau G30S 1965, termasuk tawaran memulihkan status kewarganegaraannya sebagai korban yang ada di luar negeri.
"Karena kita sudah tua-tua, kita tidak lama lagi hidup di dunia ini jadi kalau saya ditawari dwikewarganegaan saya mau. Karena bayangkan saja, kalau saya mau ke Indonesia menengok - bukan pulang ya - menengok tanah air tercinta, menengok keluarga tercinta saya harus mengajukan permohonan visa, saya harus bayar.
"Bukan uangnya, tapi perasaan. Saya merasa sedih mau menengok negara sendiri harus minta izin," kata Soejono dari kediamannya di Praha, ibu kota Republik Ceko.

Sumber gambar, Dokumentasi Soegeng Soejono
Negara di Eropa timur itu telah menjadi rumahnya dan telah memberikan perlindungan kepada Soejono sejak status WNI-nya dicabut pasca-peristiwa G30 S 1965.
Ketika itu, diperkirakan beberapa ribu pemuda dan pemudi Indonesia sedang bersemangat tinggi mengisi masa muda berkuliah di luar negeri. Ada yang mendapat beasiswa ikatan dinas dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, seperti Soejono.
Sebagian lagi dikirim lembaga-lembaga pemerintah lain, dikirim Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi lainnya.
Bukan hanya mahasiswa, delegasi Indonesia yang tengah menghadiri acara internasional dan para diplomat era pemeritahan Sukarno pun kala itu tidak bisa pulang.
Pasalnya, setelah melewati proses screening atau penyaringan di kedutaan-kedutaan Indonesia, mereka dianggap terlibat PKI, dicap komunis, atau menunjukkan mereka tidak mendukung Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.
Konsekuensinya, paspor mereka ditahan, biasanya oleh atase militer KBRI. Dalam sekejab mereka menjadi orang-orang Indonesia tanpa punya kewarganegaraan.

Sumber gambar, Dokumentasi Soeyono
Soejono merasa beruntung diterima menjadi warga negara Ceko sesudah menyandang gelar tanpa kewarganegaraan selama bertahun-tahun. Kuliah di Universitas Charles, Soejono mengambil jurusan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Kejiwaan untuk Anak-Anak.
Dia menikah dengan seorang perempuan setempat dan mempunyai dua keturunan. Di masa tuanya, Soejono merasa bahagia mendampingi cucu-cucunya tumbuh.
"Intinya kalau ditawari dwikewarganegaraan saya terima. Tapi kalau tidak, saya lanjutkan saja karena saya di negara ini sudah seperti negara saya yang kedua. Dan saya hidup bahagia dengan keluarga dan di negara ini saya sudah seperti di rumah sendiri," jelasnya.
Akan tetapi, Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perkecualiannya adalah anak-anak dari hasil perkawinan campur. Itu pun sampai usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak berkewarganegaraan ganda tersebut harus menentukan pilihan menjadi WNI, atau WNA.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tertanggal 15 Maret tentang pelaksanaan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi tidak menyebut kemungkinan kewarganegaraan ganda seperti yang dikehendaki Soejono.
Presiden menugaskan menteri luar negeri untuk memberikan layanan dokumen kewarganegaraan kepada korban pelanggaran HAM berat yang tinggal di luar negeri atau eksil, di samping melakukan pendataan.
"Melakukan verifikasi data dan memberikan prioritas layanan untuk memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan terhadap korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang berada di luar negeri," kata Presiden Jokowi dalam inpresnya.
Kemudian, menteri hukum dan HAM diinstruksikan memberikan prioritas layanan dalam memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan kepada korban dan ahli warisnya.
Di Republik Ceko, hanya sekitar 14 eksil politik yang tersisa, kata Soejono. Mayoritas berusia lanjut. Soejono sendiri, kelahiran Madiun, Jawa Timur, merupakan satu-satunya dari 13 bersaudara yang masih hidup.
Narasumber kedua saya ada di ibu kota Swedia, Stockholm. Tom Iljas satu tahun lebih muda dari Soejono. Keduanya tidak saling berkontak, tetapi bernasib sama.
Tom juga telah mendapat kewarganegaraan Swedia sesudah hijrah dari China, tempatnya mendalami teknik pertanian.

Sumber gambar, Dokumentasi pribadi Tom Iljas
Sempat beberapa kali merintis upaya mendapatkan kembali status WNI-nya, sekarang Tom (83) menyambut datar upaya pemerintah.
"Saya sudah terbiasa mendengar demikian. Tidak kaget lagi. Tidak optimistis dan juga tidak pesimistis karena kredibilitas politisi kita kecil. Politisi kita sayang demikianlah, termasuk menteri-menteri dan presiden sekalipun. Itu sangat tidak bisa dipercaya," urai Tom dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada awal Februari.
Landasan sikap Tom adalah pengalaman. Presiden Abdurrahman Wahid, lebih popular dikenal dengan Gus Dur, berusaha mendobrak tembok-tembok pemikiran lama. Pada awal tahun 2000, Gus Dur mengirim Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra ke Belanda guna mendengarkan suara ratusan eksil sebagai bagian dari rekonsiliasi masa lalu.
"Para eksil dikumpulkan, waktu itu banyak yang masih hidup. Bertangis-tangisanlah mereka karena ada harapan bisa kembali ke tanah air dan kembali mendapatkan kewarganegaraan. Tetapi apa yang terjadi, sesudah Yusril kembali ke Indonesia? Beberapa hari kemudian dia menulis satu artikel yang cukup panjang, tentang 'bahaya komunisme'," terang Tom.
Dalam berbagai kesempatan Yusril mengatakan komunisme, sebagai ideologi, tidak akan pernah mati kendati mengalami perubahan bentuk. Kesimpulan itu ditarik sesudah mempelajari komunisme di bangku kuliah.
Hingga Gus Dur dilengserkan pada 2001, tindak lanjut pertemuan di Belanda tersebut tidak terwujud.

Sumber gambar, Getty Images
Kemudian, Tom Iljas mengaku melakukan pendekatan melalui seorang menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya itu menemui kebuntuan.
Pengalaman pahit juga menimpa Tom pada Oktober 2015. Tom hendak berziarah ke makam ayahnya, yang merupakan korban pembunuhan massal tragedi 1965 di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Belum sempat berdoa di lokasi kuburan massal, Tom diinterogasi aparat dan kemudian dideportasi.
Ayahnya adalah anggota PKI, meskipun keanggotaannya lebih dilandasi pada semangat menentang kolonialisme, tanpa memahami ideologi komunisme itu sendiri, tutur Tom.
Kaitan itu pula yang turut membuatnya terdampar di China pasca 1965, walaupun studinya sudah rampung. Pilihannya, pulang ke Indonesia dengan risiko ditahan dan tidak diketahui nasibnya, sebagaimana terjadi pada mahasiswa yang dianggap terlibat PKI atau berhaluan kiri.
Tom meminta perpanjangan izin tinggal di China dan akhirnya mengajukan suaka di Swedia.
Yang menarik, ketika memijakkan kaki di tanah air mereka, baik Soejono maupun Tom Iljas sama-sama menggambarkan perjalanan itu bukan sebagai kegiatan pulang. Soejono menyebutnya menengok tanah air. Tom cenderung menggunakan istilah berkunjung ke tanah air.
Soejono pertama kali kembali ke negara asalnya sesudah rezim Orde Baru tumbang pada 1998. Dia ingat begitu turun dari kapal terbang di Bandara Soekarno Hatta, dia hendak memenuhi nazarnya mencium tanah Indonesia. Malang, lapisan beton yang ditemui. Baru di luar gedung terminal Soejono menemukan tanah, tapi becek pula.
"Setelah berjalan agak jauh, akhirnya saya menemukan tanah dan saya cium tanah itu," kenang Soejono.
Suara dari Belanda, konsentrasi eksil 65
Belanda diperkirakan paling banyak menampung eksil 65, walaupun selama ini tidak ada pendataan menyeluruh. Banyak warga Indonesia yang terhalang pulang dan yang semula tersebar di banyak negara akhirnya mencari suaka ke Belanda dan terkonsentrasi di sana.
Menurut sesepuh eksil di Belanda, Sungkono, sekarang hanya terdapat sekitar 50 eksil langsung (tidak termasuk keturunan) yang masih hidup di negara itu. Mayoritas eksil sudah tutup usia.

Sumber gambar, Dokumentasi Sungkono
Sikap Sungkono (84) tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat tragedi 1965 tidak pernah berubah, yakni penyelesaian hendaknya dilakukan atas dasar usaha yang serius, adil dan berdasarkan pengungkapan kebenaran.
Dengan demikian, upaya terbaru untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat belum menyentuh ke pangkal masalah.
"Kalau hanya tujuannya untuk memberikan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi itu dengan sendirinya harus begitu. Yang pokok adalah langkah-langkah untuk benar-benar mengungkapkan kebenaran. Harapan kami itu," cetusnya dalam percakapan melalui telepon pada Senin (20/02).
Ditambahkan, tuntutan pokok para eksil adalah mengungkap tragedi skala nasional tahun 1965-1966.
"Itu pelanggaran yang sistematis sampai seluruh pelosok tanah air kita tidak ada yang terlewat dan bentuknya sangat mengerikan; dari manusia yang tidak tahu dosanya dibunuh, ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa, bahkan kaum wanita yang dicurigai diperkosa, dan masih banyak lagi yang di luar peri kemanusiaan. Ini belum mereka ungkap," tegasnya.

Sumber gambar, Getty Images
Pada Sabtu 11 Februari lalu, Sungkono bersama puluhan eksil menggelar kumpulan di Amsterdam untuk bertukar pemahaman mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk memulihkan hak-hak mereka.
Untuk itu, mereka memutar rekaman pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikeluarkan di Jakarta pada 11 Januari lalu. Ketika menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM), Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi dalam berbagai peristiwa di Indonesia.
"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," kata Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, pemerintah berjanji memulihkan hak-hak para korban, termasuk pelarian politik yang terdampak peristiwa 1965-1966.
Kendati demikian, Sungkono berpendapat langkah yudisial harus tetap diutamakan, bukan seperti yang ditawarkan sekarang.
"Kalau diibaratkan penyelesaian itu sebuah pohon, maka soal itu hanya rantingnya. Sedangkan batangnya, cabangnya belum disentuh," katanya melalui sambungan telepon.

Sumber gambar, Lea Pamungkas
Masih di Belanda, saya menelepon Aminah Idris, warga Indonesia yang juga terhalang pulang ketika studi di Bulgaria dan kemudian menetap di Belanda.
Apa yang disampaikannya sama dengan sikap Sungkono.
"Rencana itu sebetulnya ada baiknya, cuma kalau tidak dibongkar siapa yang salah dan siapa yang tidak, ya bagaimana?"
Tuntutan untuk tuntaskan pokok masalah peristiwa 65, bukan dari buntut
Sepaham dengan Sungkono dan Aminah Idris, Tom Iljas berkeyakinan bahwa memulihkan kewarganageraan sama artinya menyelesaikan masalah tanpa menyentuh pokok persoalan padahal pengungkapan kebenaran adalah langkah yang genting.
"Menurut saya, dengan cara ini maka yang akan diselesaikan adalah buntutnya dulu, eksesnya. Bukan masalah pokoknya," kata Tom.
"Di setiap pelosok tanah air di mana ada pendukung Bung Karno, atau orang-orang PKI atau simpatisannya di situ terjadi pembunuhan, penangkapan. Bersifat nasional sehingga penyelesaiannya mestinya, logisnya juga secara nasional," imbuh pensiunan karyawan Scania, produsen otomotif besar Swedia itu.

Sumber gambar, Dokumentasi Tom Iljas
Adapun ekses yang dimaksud bagi orang-orang seperti dirinya adalah pencabutan paspor sehingga tidak bisa bepergian, atau harus mencari paspor asing.
"Paspor saya sendiri ditahan oleh atase militer di KBRI Peking pada waktu itu," jelasnya.
Tom menerima catatan dari KBRI bahwa kalau ingin pulang, dia akan diberi surat pengganti paspor dengan syarat harus terbang langsung ke Jakarta, tanpa transit di mana pun. "Itu jelas maksudnya apa. Mau ditahan toh."
Dengan upaya Presiden Jokowi menemui para korban peristiwa 1965, Tom khawatir penyelesaian yudisial justru akan terkubur.
"Adanya pengakuan Pak Jokowi itu sudah kemajuan kecil dibanding sebelum ini tidak ada apa-apa, bahwa mengakui adanya pelanggaran berat tahun 1965-1966 tapi di situ tak disebut siapa yang membunuh siapa, aktornya siapa, korbannya siapa. Jaminannya bahwa itu tidak akan terulang apa, bahwa kalau orang-orang ini pulang tidak dideportasi lagi. Jaminannya apa?"
Baca juga:
Pendapat serupa juga diutarakan Soegeng Soejono di Praha. Pernyataan Presiden Jokowi tentang adanya pelanggaran HAM berat merupakan kemajuan, namun yang penting adalah tindak lanjutnya.
"Saya ingin supaya tuntas, adil dan beradab dan sebagainya. Sebetulnya tidak cukup dengan menyatakan bahwa terjadi, karena kalau kita pelajari sejarah zaman Gus Dur mengakui itu, dia terus dihantam sampai dia jatuh."
Belajar dari pelengseran Gus Dur tersebut, Soejono menganalisis bahwa Presiden Jokowi tidak bisa membuat pengakuan pelanggaran HAM berat di masa jabatan pertama, melainkan menjelang akhir jabatan kedua.
"Tetapi sebentar lagi kekuatan Pak Jokowi akan digantikan kekuatan yang lain. Terus sampai di mana nanti penyelesaiannya ini?" tanya Soejono dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia di London, Rohmatin Bonasir.
"Bahwa ada pengakuan itu pun sudah kemajuan dan saya bahagia saya masih ada di dunia ini dan bisa mendengarkan langsung tetapi saya ingin masih berada di dunia ini untuk melihat dan menyaksikan bagaimana penyelesainnya secara tuntas dan adil dan beradab," tambahnya.
Semangat orang-orang 'terbuang'
Dalam percakapan saya dengan sejumlah eksil politik di atas, terkesan bahwa pada umumnya mereka tidak menunjukkan sikap getir atau dendam karena menjadi orang-orang 'terbuang'.
Mantan Presiden Gus Dur menyebut mereka orang-orang 'kelayapan' karena harus berkelana dari satu negara ke negara lain sesudah tidak punya kewarganegaraan. Mereka juga disebut kaum intelektual yang terbuang atau juga tahanan politik.
Soejono melandasi sikap positifnya pada keyakinan bahwa yang dilakukan benar. Dia menolak mengutuk Presiden Sukarno yang pemerintahannya memungkinkan generasi muda bersekolah di luar negeri untuk kemudian mengaplikasikan ilmu di dalam negeri.
"Sebetulnya kita, seperti saya yang dicabut paspor, tapi saya jauh dari tanah air, jauh dari marabahaya, jauh dari todongan bedil, tidak langsung menghadapi bahaya-bahaya dibantai, disiksa, dipenjara seperti orang-orang di tanah air.
"Dan, kalau bisa kita berjuang memerangi namanya rezim Orde Baru yang sifatnya menurut saya pribadi adalah rezim yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia," papar Soejono.
Begitupun, dia merasa sebagai orang Indonesia tulen, bahkan perasaan keindonesiaannya lebih besar daripada kalau tinggal di Indonesia. Dia menemani orang-orang Indonesia yang berkunjung ke Praha, mengikuti acara-acara di KBRI ataupun kegiatan yang ada kaitannya dengan Indonesia.
Soejono adalah salah satu sosok eksil 1965 yang kerap meladeni wawancara. Baginya itulah salah satu cara "meluruskan sejarah yang telah dibengkokkan".

Sumber gambar, Dokumentasi Aminah Idris
Demikian pula dengan Aminah Idris di Belanda. Dia dengan senang hati menceritakan peristiwa yang menyita masa mudanya. Penjelasan-penjelasannya diselangi tawa.
Sejatinya Aminah merasakan kegetiran "tapi apa boleh buat".
"Kami sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan seperti abu di atas tunggul. Itu juga yang selalu dikatakan suami saya. Kalau ada angin bertiup, kita terbawa. Seperti itulah nasib seorang tanpa kewarganegaraan," ungkap perempuan asli Solo tersebut.
Menggunakan perumpamaan itu, Aminah dan keluarga harus boyong dari Bulgaria ke Belanda pada 1990. Gerakan menentang orang asing di Bulgaria tahun 1988 membuat pasangan itu angkat kaki dari negara tempat mereka menimba ilmu dan pada awalnya memberikan perlindungan.
Aminah kehilangan status WNI ketika menempuh studi di Bulgaria. Sesudah tragedi 1965, dia diundang ke KBRI Sofia. Di sana dia mendapat penjelasan tentang pergantian kekuasaan di Indonesia. Lantas dia diminta meneken formulir dukungan kepada pemerintahan pimpinan Presiden Suharto. Dia menolak.
Dia diundang lagi ke KBRI, sampai beberapa kali. Sikapnya tetap sama.
"Kami dikirim oleh pemerintahan Soekarno. Kami sudah berunding dengan teman-teman mahasiswa lainnya dan begitulah kami menentukan sikap," kata Aminah menjawab pertanyaan BBC News Indonesia apa yang melandasi penolakan mendukung pemerintahan baru kala itu.

Sumber gambar, Lea Pamungkas
Adapun Sungkono seolah mendapat amunisi menjaga pikiran positif dari upaya-upaya untuk meluruskan sejarah Indonesia terkait peristiwa 1965-1966. Meski lanjut usia, dia tetap aktif di sejumlah organisasi di antaranya Perhimpunan Persaudaraan, Lembaga Perjuangan Korban 65 dan Watch65.
"Kita tidak menyerah dengan nasib ini. Kita harus berjuang untuk keadilan, kebenaran. Banyak di kalangan kami masih melakukan langkah itu. Jadi ini tampaknya juga memberikan energi bagi kami untuk hidup secara optimis," paparnya.
Bagaimanapun pada saat yang sama Sungkono juga bertarung melawan tekanan batin. Tekanan batin yang paling berat, menurutnya, terjadi akibat hubungan dengan keluarga di Indonesia terputus. Dia mengingat tradisi warga di kampung asalnya di Sumatera Utara berbondong-bondong menjenguk tetangga yang sakit dan menguburkan mereka yang meninggal dunia.
"Tapi untuk orang tua kita sendiri, kita tidak menyaksikan mereka meninggal dunia, apalagi menguburnya secara naluri tadi. Itu selalu menggugat hati kita, sedih. Itu penderitaan batin," ungkap Sungkono dalam percakapan dengan BBC News Indonesia.
Tidak semua eksil bersedia berbagi lembaran kelam yang mereka tapaki. Sebagian menolak memberikan wawancara karena khawatir sanak keluarga di Indonesia hidup dalam stigma dan dikucilkan.
Hingga kini masih ada yang percaya bahwa suara eksil bisa menyebabkan kebangkitan kembali komunisme. Menjelang hajatan politik, jargon 'awas bahaya laten komunis' kerap dihembuskan.
Propaganda Orde Baru yang menjadikan paham, kelompok atau orang-orang komunis sebagai musuh bersama tampak terpatri di alam bawah sadar masyarakat. Demikian pula prasangka buruk tentang orang-orang yang dicap komunis atau orang berhaluan kiri.
Namun muncul pula upaya-upaya generasi muda, akademisi, aktivis untuk mencari kebenaran dalam sejarah Indonesia. Dokumen-dokumen menyebutkan jumlah korban jiwa akibat apa yang digambarkan sebagai perang melawan komunis berkisar antara 500.000 hingga satu juta jiwa.
What's Your Reaction?