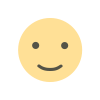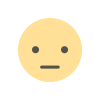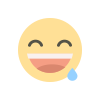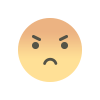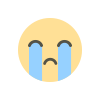Peristiwa 1965: Pemerintah beri visa gratis, para eksil tuntut 'permintaan maaf dan pengungkapan kebenaran' - 'Kalau hanya sampai sini, tak bisa dianggap selesai'
Pemerintah menawarkan kemudahan layanan imigrasi bagi eksil 1965 yang ingin kembali ke Indonesia sebagai bentuk "pemulihan hak kewarganegaraan mereka". Tetapi bagi sebagian eksil, langkah itu "tidak cukup" memulihkan penderitaan mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat.


Sumber gambar, GETTY IMAGES
Pemerintah menawarkan kemudahan layanan imigrasi bagi eksil 1965 yang ingin kembali ke Indonesia sebagai bentuk "pemulihan hak kewarganegaraan" mereka. Tetapi bagi sebagian eksil, langkah itu "tidak cukup" memulihkan penderitaan mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat.
Di hadapan dua menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo, para eksil menuntut secara langsung permintaan maaf negara dan pengungkapan kebenaran atas apa yang menimpa mereka.
Pertemuan antara para eksil dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly itu berlangsung di Amsterdam pada Minggu (27/08), tepat dua bulan setelah pemerintah meluncurkan program pemulihan hak-hak korban 12 kasus pelanggaran HAM berat.
Agenda utamanya adalah penyampaian fasilitas layanan imigrasi untuk memudahkan para eksil yang ingin kembali ke Indonesia, sebagai upaya di tengah kebuntuan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Fasilitas itu berupa visa gratis untuk melakukan kunjungan berkali-kali (multiple entry) serta izin tinggal sementara yang bisa berlaku hingga enam tahun.
“Pemerintah hanya mau menyampaikan mari kita perbaiki, mari kita sembuhkan luka yang lama. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian yang dulu mungkin sangat muskil, sangat sulit dilakukan,” kata Yasonna dalam pertemuan tersebut.
Namun bagi Sungkono, salah satu eks mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang kini menetap di Amsterdam, negara masih berutang permintaan maaf dan pengungkapan kebenaran.
"Yang saya tuntut adalah keadilan, bukan soal teknis tadi, visa gratis itu, saya tidak berpikir itu sekarang. Yang saya pikirkan, bagaimana tanggung jawab negara kepada kami, yang dulu tugas kami belajar secara tekun kok diperlakukan sewenang-wenang?” kata Sungkono di tengah dialog.
Tuntutan senada disampaikan oleh sejumlah eksil lainnya yang hadir. Pemerintah diminta mencabut TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme yang dinilai sebagai penyebab lekatnya stigma terhadap para korban peristiwa 1965.
Selain itu, mengemuka pula desakan penulisan ulang sejarah serta penindakan hukum terhadap para pelaku, yang hingga kini belum membuahkan hasil.
Namun Mahfud meresponsnya dengan menyatakan bahwa pemerintah Orde Baru-lah "yang seharusnya meminta maaf". Mahfud juga tak sepakat soal penulisan ulang sejarah "sebagai kebijakan resmi pemerintah".
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan respons itu, yang dia sebut menunjukkan "masih rendahnya kemauan politik pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat".
"Kami belum melihat kesungguhan dan ketulusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Usman.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro yang dihubungi secara terpisah, mengatakan bahwa apa yang disampaikan para eksil "bukanlah harapan yang mudah untuk dipenuhi oleh negara dalam waktu singkat".
Apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para eksil?
Sungkono: ‘Mengakui dosa sekian besarnya, kok tanpa minta maaf?’

Sumber gambar, DOKUMENTASI SUNGKONO
Sungkono meninggalkan Indonesia untuk berkuliah di jurusan teknik mesin Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa, Moskow, Rusia pada 1962.
Pada 1966, setelah menjalani skrining oleh pemerintah Orde Baru, paspornya dicabut. Sungkono kemudian dinyatakan tidak boleh pulang.
"Saya harus tinggal di negeri asing, harus tinggal sama orang-orang asing. Saya terasa seperti musafir, harus berkenala ke tempat-tempat lain," kata Sungkono yang akhirnya mulai menetap di Amsterdam sejak 1981.
Begitu mendengar pengakuan Presiden Jokowi terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat pada akhir 2022 lalu, Sungkono sempat merasa hal itu sebagai "hal yang luar biasa".
"Tapi saya merasa pernyataan Pak Jokowi ini belum lengkap. Kalau sudah mengakui dosa sekian besarnya, kok tanpa minta maaf? Hanya menyesali," katanya.
"Ini kejahatan besar di suatu negara kok tanpa menyatakan minta maaf. Ini saya tuntut, tanggung jawab negara itu harus dipikul oleh kepala negara."
Sampai akhirnya dialog langsung dengan pemerintah terwujud, Sungkono dan istrinya, Siti Krisnowati mengaku tak puas dengan apa yang disampaikan pemerintah.
Dihubungi usai menghadiri acara, Sungkono menyayangkan sikap pemerintah yang enggan meminta maaf.
"[Pemerintah] sangat membatasi pemulihan itu pada hal-hal praktis. Kalau betul-betul tujuannya untuk mengungkapkan atau menuntaskan kejahatan, walaupun sulit, tapi tidak bisa kalau hanya sampai sini dianggap selesai," kata dia.
Bagi Sungkono pribadi, kemudahan layanan imigrasi itu "sudah tidak mungkin" dia manfaatkan.
"Saya sudah tua, enggak punya apa-apa di sana. Kalau saya diberi kemudahan tertentu apa bisa menjamin saya bisa hidup normal di sana? Apa itu bisa menjadi jaminan keamanan bagi saya?" tanyanya.
Tom Iljas: ‘Tidak ada jaminan kami aman’

Sumber gambar, DOKUMENTASI TOM ILJAS
Bagi Tom Iljas, upaya pemerintah ini tak bisa disebut sebagai "penyelesaian nonyudisial", melainkan sebatas "penanganan kompensasi kepada korban 1965".
"Judulnya sangat cerdik dan menyesatkan. Karena pembukaannya saja penyelesaian, berarti kalau ini diselenggarakan berarti masalahnya sudah selesai," katanya.
Tom adalah salah satu eksil 1965 yang kini menetap di Swedia.
Baginya, fasilitas layanan imigrasi yang diberikan pemerintah "tidak menjamin" keamanan para eksil untuk pulang ke Tanah Air sepanjang stigma yang melekatkan mereka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih menjamur.
Tom pernah dideportasi dari Indonesia pada 11 Oktober 2015, ketika berziarah ke makam orang tuanya di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Tom kemudian dicekal selama satu tahun ke Indonesia.
“Itu sudah zamannya Pak Jokowi saya dicekal. Kenapa itu terjadi? Karena payung hukum itu masih ada, TAP MPRS itu. Selama payung hukum itu masih ada, polisi, tentara bisa berbuat apa saja kepada para korban,” kata Tom.
“Jadi selama TAP MPRS ini tidak dicabut, tidak ada jaminan kami akan aman di Indonesia”.
Sri Tunruang: “Saya masih dimaki, ‘Dasar tante Gerwani’”
Stigma negatif juga dirasakan oleh Sri Tunruang alias Ning, yang kini menetap di Aachen, Jerman.
Ning masih menjadi anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) hingga kini.
“Saya merasakan yang namanya stigma, yang namanya kebencian. Kalau saya salah tingkah mereka bilang, ‘Dasar Gerwani’. [Pada tahun] 2015 saya masih dimaki, ‘Dasar tante Gerwani’ hanya karena saya beda pemikiran,” kata dia.
Menurut Ning, pengungkapan kebenaran baik secara yudisial maupun nonyudisial "tetap harus dilakukan" untuk menghapus stima tersebut.
"Tanpa pengungkapan kebenaran, kita enggak bisa maju secara yudisial maupun nonyudisial," tutur Ning.
Willy Wirantaprawira: 'Saya bisa ikut pemilu tahun depan'
Sementara itu, Willy Wirantaprawira, yang kini menetap di Jerman, mengaku "mencoba realistis" dengan menerima tawaran pemerintah terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang menerimanya.
Willy dulunya merupakan mahasiswa ikatan dinas ke Uni Soviet. Dia sempat kembali ke Indonesia setelah lulus pada 1968. Namun statusnya sebagai eks mahid membuat Willy harus melalui skrining oleh Badan Intelijen, bahkan pernah diinterogasi.
Situasi itu membuat Willy kembali ke Uni Soviet untuk beasiswa doktoral. Paspornya dicabut oleh KBRI Moskow pada 1970.
"Sampai sekarang terus terang saja kalau menunggu sampai yudisial diselesaikan, sampai kiamat pun tidak akan terjadi. Sedangkan umur saya, sudah 87 tahun, lusa sudah bisa mati, enggak bisa merasakan keadilan," kata Willy.
"Saya menganggap sangat baik ide pemerintah sekarang untuk menolong kami, kembalikan warga negara saya, sehingga saya bisa ikut pemilu tahun depan, bisa berlibur ke Indonesia bukan sebagai turis, tapi sebagai bangsa Indonesia."
Bagaimana tanggapan pemerintah?
Menurut Mahfud, tuntutan untuk meminta maaf itu tak tepat ditujukan kepada pemerintah pascareformasi.
Pemerintah, kata dia, "telah berupaya" menghapus stigma yang melekat pada korban 1965. Salah satunya dengan menghapus kebijakan penelitian khusus terhadap eks PKI, yang dulu membuat mereka sukar bekerja.
"Jangan kita yang disuruh minta maaf, wong kita yang buka semua, kok kita yang disuruh minta maaf? Wong kita yang jatuhkan rezim itu," kata Mahfud di hadapan para eksil.
Sedangkan terkait tuntutan untuk penulisan ulang sejarah, yang menurut para eksil telah diputarbalikkan, Mahfud menyatakan "tak setuju".
"Ganti pemerintah sejarahnya beda-beda kok. Negara akan menyediakan biaya penelitian untuk penulisan sejarah, silakan. Tapi [hasilnya] bukan sikap negara penelitian itu," katanya.
Negara, sambung Mahfud, "hanya akan menegakkan hukumnya".
Namun terkait upaya pidana terhadap para pelaku, Mahfud juga mengatakan proses itu sudah diupayakan meski belum membuahkan hasil karena tersendat pembuktian.
"Sudah puluhan tahun kita usahakan. Kalau hukum pidana, pelakunya kan harus jelas. Pelakunya sudah meninggal semua."
"Kalau di dalam hukum pidana, enggak boleh dihukum orang lain yang bukan pelaku langsungnya. Kalau rezimnya sudah dihukum secara politik, sudah dijatuhkan, sudah selesai. Pidananya mau menghukum siapa?" kata Mahfud.
'Seremonial belaka'
Respons pemerintah di hadapan para eksil itu dikritik oleh Amnesty International Indonesia, karena dianggap "sinis" terhadap harapan para korban akan hak-hak mereka.
"Respons itu kurang mencerminkan pemahaman yang benar terhadap hukum hak asasi manusia baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dan dari situ terlihat bahwa political will pemerintah masih rendah," kata Usman Hamid.
Dihubungi terpisah, Hendardi dari Setara Institute menilai upaya nonyudisial ini pada akhirnya menjadi semacam "seremonial belaka" tanpa benar-benar menampung aspirasi para korban.
"Karena hak korban yang paling utama untuk mendapatkan keadilan dan pengungkapan kebenaran, tidak terjawab hak itu," tuturnya.
Pemerintah juga dinilai tak boleh melimpahkan beban permintaan maaf kepada rezim yang telah jatuh. Sebab tanpa permintaan maaf, maka pengungkapan kebenaran juga akan sulit terwujud.
"Yang dialami oleh para eksil, memang tidak mudah diungkap secara hukum, itu kita pahami. Tapi negara dalam periode pemerintahan kapanpun seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM," kata Hendardi.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai kemudahan izin masuk ke Indonesia dan pemberian surat keterangan korban pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pemulihan "yang dapat segera dilakukan pemerintah".
"Bentuk-bentuk pemulihan yang membutuhkan landasan hukum dan keputusan serta konsensus politik yang lebih kompleks, sepertinya sulit untuk segera dilakukan," kata Atnike.
Apalagi mengingat jumlah korbannya yang sangat luas, sehingga "tidak mungkin" diselesaikan dalam waktu singkat.
Namun dia berharap inisiatif nonyudisial ini akan berkelanjutan dan dijadikan peluang untuk melanjutkan upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di masa mendatang.
What's Your Reaction?