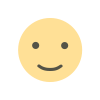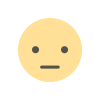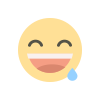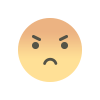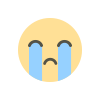Plaza Senayan
Maka jelas, mal bukanlah sekadar lokus ekonomi tempat jual-beli barang, melainkan juga arena provokasi pikiran, jangkar dari sensasi dan memori, tak heran dulu pernah dijuluki “katedral modernisme”.
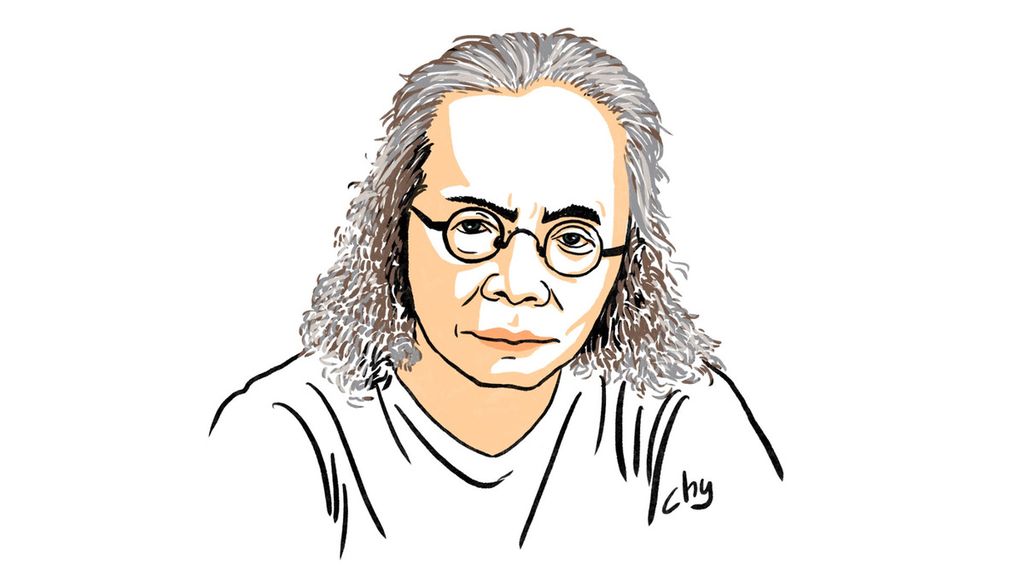
Bre Redana
Cukup lama saya tidak jumpa Ariel Heryanto, profesor emeritus yang pernah mengajar di sejumlah universitas di Australia. Sejak pandemi, baru bulan lalu ia ke Jakarta bersama istrinya, Yanti. Dia mengajak saya dan Vivi bertemu, makan siang di Plaza Senayan. Ia juga undang Sarie, teman yang belum lama ketemu dengannya di Melbourne.
Bersamanya segala sesuatu segera direfleksikan untuk menggambarkan sebuah gejala sosial lebih luas selain kadang untuk menertawakan diri sendiri. Ketika saya katakan bahwa pada zaman serba online ini bertemu dan reriungan tiba-tiba bisa menjelma menjadi sebuah peristiwa budaya, ia menyambar, terlebih di mal—tonggak penting modernisme.
”Pernah aku ingin mengadakan seminar, judulnya ‘Nineteen Twenties’ (1920-an). Segala hal yang kita alami sekarang pernah terjadi pada era tersebut,” katanya. Dia sebut pemikiran-pemikiran kala itu dari Marx, Freud, Tan Malaka, dan lain-lain sampai berdirinya PKI.
Layaknya dosen tengah mengajar ia menerangkan kepada Sarie mal pertama muncul di Amerika tahun 1920-an, berkoinsidensi dengan gelombang feminisme.
Tentang itu bisa ditelusuri lebih lanjut dari berbagai referensi yang kini serba mudah didapat. Dengan ratifikasi amendemen, sejak itu di Amerika perempuan memiliki apa yang tidak mereka punyai sebelumnya, yakni hak pilih. Bersamaan emansipasi politik ini perempuan juga kian leluasa keluar dari lingkungan domestik, termasuk keluyuran di mal yang waktu itu masih merupakan gejala baru.
Baca Juga: Apa Pantas Perempuan Keluar Malam Sendirian
Maka jelas, mal bukanlah sekadar lokus ekonomi tempat jual-beli barang, melainkan juga arena provokasi pikiran, jangkar dari sensasi dan memori, tak heran dulu pernah dijuluki ”katedral modernisme”.
”Itu sebabnya area perfume ditempatkan dekat pintu masuk. Konon cewek suka yang wangi-wangi,” saya menambah dengan guyonan.
Kebetulan saya tengah membaca buku karya penerima Nobel Sastra, Annie Ernaux, Look At the Lights, My Love (Yale University, 2023). Di situ Ernaux melihat konstruksi diri dan masyarakatnya dalam relasi dengan pengalaman di tempat yang sering diabaikan orang justru karena sebegitu sehari-harinya: pusat perbelanjaan.
Tanpa sadar, begitu menurut dia, kita memilih obyek ataupun tempat-tempat bagi memori sesuai spirit atau semangat zaman yang tengah kita jalani. Kita menentukan mana yang layak diingat atau tidak diiringi apa-apa yang tersedia, yang secara dramatik membuat kenangan lebih hidup, misalnya buku, lagu, film, dan sebagainya.
Dengan cara demikian, sejarah bisa dilihat tidak melulu semata-mata sebagai kronik peristiwa-peristiwa besar melainkan sebagai kronik kesadaran. Bukan peristiwa besar atau retorik-retorik kosong yang membentuk kesadaran kita, melainkan tindakan dan pengalaman.
Saya baru saja menerima kiriman buku gres Sejarah Mati di Kampung Kami (Pojok Cerpen dan Tanda Baca, Juni 2023). Ditulis oleh Nezar Patria, di situ wacana konvensional tentang sejarah juga ditinggalkan.
Baca Juga: Jangan sampai Jadi Negeri Pejabat
Melalui buku ini Nezar mencoba mengungkap kesadaran dirinya mengenai Aceh, jurnalisme, dan demokrasi tidak melalui peristiwa-peristiwa besar, tetapi hal-hal kecil sehari-hari: pertetanggaan di Kampung Mulia, Banda Aceh; pabrik sirop di lingkungannya; bioskop di Lhokseumawe yang saya pernah mengenalnya; dan lain-lain.
Tak ketinggalan sesuai disiplin akademiknya semasa kuliah, Nezar mengaitkan kesadaran tokoh Gerakan Aceh Merdeka pada zamannya, Hasan Tiro, dengan apa yang ditulis oleh yang bersangkutan dalam catatan hariannya, yakni Nietzsche. Atau bagaimana dia melihat ”kesadaran politik baru” masyarakat Aceh pada masa transisi politik tahun 1998, dengan mengutip Gramsci, ketika kekuasaan lama sedang sekarat, tetapi yang baru belum bertumbuh.
Soal kesadaran ini menjadi kian problematik terlebih di era digital di mana orang (mudah-mudahan) menyadari bahwa yang nyata dan tidak nyata, kebenaran dan kebohongan, kesejatian dan kepalsuan, makin lebur jadi satu.
Menjadi hak setiap individu untuk menentukan engagement, dengan apa ia hendak menautkan hidupnya. Dengan uang dan jabatan? Dengan kepentingan politik sesaat? Dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kini didewakan?
Sampai sejauh ini, bagi saya, yang paling afdal adalah menautkan diri dengan kesadaran, imajinasi, dan kebebasan. Biar tetap bisa tertawa-tawa termasuk menertawakan diri sendiri di tengah mal yang sebenarnya mengandung begitu banyak paradoks modernisme.
What's Your Reaction?