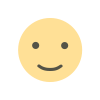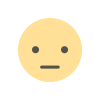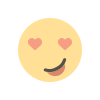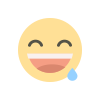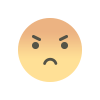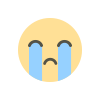Bahasa, Peristiwa, dan Tafsir
Beragam peristiwa yang terjadi di realitas menjadi titik keberangkatan Setyaningsih dalam mengurus keberadaan bahasa. Ia memberikan tafsir dengan jeli dengan menguatkannya pada keberadaan kamus, novel, puisi, film, hingga buku teks ilmiah.
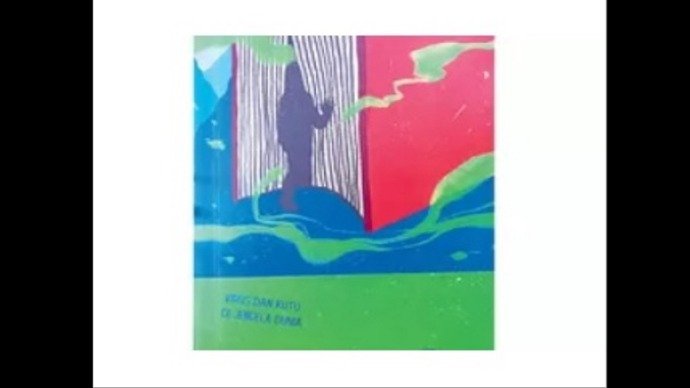
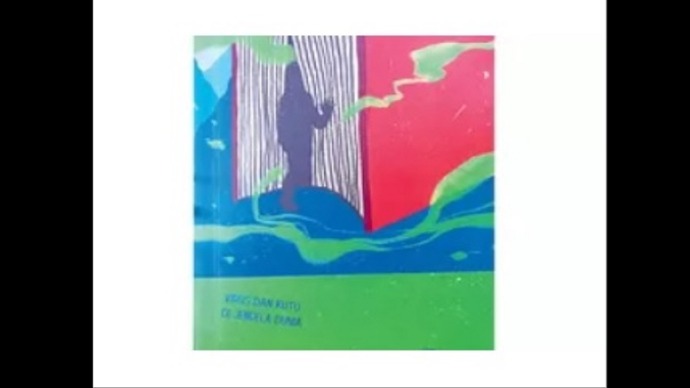
Oleh: JOKO PRIYONO*
Beragam peristiwa yang terjadi di realitas menjadi titik keberangkatan Setyaningsih dalam mengurus keberadaan bahasa. Ia memberikan tafsir dengan jeli dengan menguatkannya pada keberadaan kamus, novel, puisi, film, hingga buku teks ilmiah.
PENGALAMAN kita bersekolah dengan keberadaan pelajaran bahasa Indonesia pernah memberi keyakinan bahwa pelajaran itu penuh tanda tanya. Sebab, meski hidup di Indonesia, kita masih dibebani akan diskursus mengenai bahasa Indonesia.
Ketika melihat pembacaan dalam ruang publik, akhirnya kita sadar dan mengerti bahwa bahasa Indonesia tak sesederhana itu. Dalam diskursus pasca kebenaran dengan ditandai melesatnya perkembangan media sosial, fakta yang tak dapat ditampik adalah bahasa Indonesia membutuhkan telaah mendalam.
Namun, acap kali kita hanya terjebak pada narasi tunggal, sebagaimana pendefinisian bahasa Indonesia yang ditafsir oleh negara: baik dan benar –yang penuh klise. Kenyataan itu misalnya pernah digugat oleh Aditya Surya Putra dalam majalah Basis edisi nomor 05-06 tahun 2011. Di rubrik ”Fotolinguagrafi”, ia menghadirkan beberapa foto dan uraian dalam tulisan berjudul ”Utamakan Bahasa Indonesia”.
Ia menemui paradoks ketika anjuran berbahasa Indonesia yang baik dan benar kadang dilanggar oleh lembaga maupun dinas yang notabene berada di bawah ”Pusat Bahasa”. Ia hanya bisa pasrah dengan berucap: ”Bila demikian, tak heran, jargon ’baik dan benar’ hanya tinggal jargon.”
Pernyataan itu tentu memberikan makna tersirat bahwa dalam hiruk pikuk perkembangan zaman, bahasa tidak sebatas anjuran, perintah, dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, lebih dari itu.
Ini relevan saat kita menyimak buku garapan Setyaningsih. Beragam peristiwa yang terjadi di realitas menjadi titik keberangkatannya dalam mengurus keberadaan bahasa. Ia kemudian memberikan tafsir dengan jeli dengan menguatkannya pada keberadaan kamus, novel, puisi, film, hingga buku teks ilmiah.
Pengakuan disampaikan olehnya: ”Berbahasa dengan ragam peristiwa dialaminya, melampaui fungsi secara baik dan benar. Bahkan dalam ketidakbaikan atau ketidakbenarannya, kita masih menemukan sisi keindahannya.” (hal viii)
Jika diambil sari pati ruang diskursus dari total 32 esai dalam buku ini, setidaknya berkelindan pada berapa tinjauan. Masing-masing adalah tempat, peristiwa politik, kuliner, media sosial, serta keberadaan perempuan. Fokus pendekatan pada tema itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun saling terkait dan memberikan pengaruh antara satu dengan lainnya.
Esai-esai mengenai tempat, misalnya berjudul ”Sragentina ke Senoparty” dan ”Slebew!”. Setyaningsih memberikan uraian perkembangan media sosial yang berpengaruh pada penuturan bahasa mengenai tempat.
Konteks dua esai itu tak lain adalah bagaimana penuturan bahasa Indonesia mengacu pada keberadaan bahasa gaul yang terjadi di kalangan anak-anak muda di beberapa daerah. Kita tahu, sejak merebaknya tren bahasa ”Jakarta Selatan” menjadi situasi yang ramai akan soal kebahasaan.
Persoalan urban menjadi sorotan dalam perubahan yang terjadi. ”Bahasa tempat menjadi penanda kosmopolitanisme yang membentengi manusia urban dan ketakutan ketinggalan zaman atau tidak dianggap hype.” (hal 47).
Ihwal itu mengingatkan pidato kebudayaan Seno Gumira Ajidarma di Dewan Kesenian Jakarta 2019. Melalui pidato berjudul ”Kebudayaan dalam Bungkus Tusuk Gigi” itu, Seno memberi tesis bahwa dalam kecamuk zaman, mereka yang berkemungkinan mudah kehilangan bahasa adalah kalangan urban.
Pada aspek keterhubungan dengan politik, dalam beberapa esai Setyaningsih, kita akan mengerti bahwa ruang politik mudah merusak makna bahasa secara serampangan.
Beberapa esai itu misalnya berjudul ”Bahasa (Politik) Pangan” dan ”Bukan Miskin, tapi Prasejahtera”. Itu membuktikan kalangan politik mudah membuat perubahan makna dari kata dan lema dengan konteks kepentingan yang terjadi. Kalangan politik mudah mencomot suatu kata dengan tujuan membangun makna untuknya.
”Politik didirikan dengan bahasa sebelum tindakan. Sepertinya tidak ada bahasa politik yang begitu dianggap jitu untuk menopang citra sekaligus menambang dukungan selain bahasa pangan.” (hal 90)
Hal lain yang terjadi dalam telaah bahasa dalam ruang politik adalah eufemisme atau penghalusan makna kata. Fenomena ini dalam sejarah politik bahasa Indonesia menjadi catatan Idy Subandy Ibrahim dan Yudi Latif (1996), ”Lewat bahasa yang digunakannya para petinggi negara bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, tetapi juga bersembunyi dari realitas dan perilaku yang sesungguhnya.”
Setyaningsih adalah seorang perempuan yang menulis. Dalam beberapa bagian di buku, ia menghadirkan isu kebahasaan dalam konteks ragam perubahan makna terhadap perempuan. Tak lain adalah objektivisme dan stereotipe yang menjadikan perempuan tidak mendapatkan ruang yang aman dalam ruang bahasa kita.
”Kesopanan, kesementaraan, dan keraguan biasanya menjadi ciri gaya bertutur perempuan. Hal ini menjadi efek kultural dan historis yang memosisikan perempuan sebagai penutur kelas dua setelah laki-laki.” (hal 104)
Keterangan itu mengingatkan kritik yang dilontarkan kosmolog dan feminis Karlina Supelli melalui esai berjudul ”Bahasa untuk Perempuan: Dunia Tersempitkan” dalam bunga rampai Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru (1998). Ketimpangan perempuan dalam persoalan bahasa ditegaskan olehnya:
”Perempuan tidak dapat membahasakan diri dengan cara seperti laki-laki dapat dengan begitu saja memetik kata-kata yang ada di dalam kamus untuk menggambarkan siapa dirinya, apa kegiatannya, dan tujuan yang ia cita-citakan.”
Dari keseluruhan tulisannya, Setyaningsih membuat daftar kata yang dijadikan acuan dalam menafsirkan peristiwa bahasa. Upaya menafsirkan itu yang menjadikannya menilik keberadaan kamus yang membentuk sejarah kebahasaan kita.
Kamus-kamus yang kerap kali kita anggap remeh dengan tak memedulikan dan membiarkan lusuh. Tilikan terhadap kamus menjadi pijakan Setyaningsih terhadap perubahan yang terjadi. Buku ini, meski tidak menjawab banyak persoalan akan bahasa, tetap penting untuk menelaah fenomena kebahasaan dalam konteks mutakhir. (*)
—
Judul : Virus dan Kutu di Jendela Dunia
Penulis : Setyaningsih
Penerbit : Rua Aksara
Cetakan : Pertama, Januari 2025
Tebal : xii + 154 halaman
ISBN : 978-623-6650-55-4
—
*) JOKO PRIYONO, Fisikawan partikelir dan budayawan, penulis buku Bersandar pada Sains (2022)
What's Your Reaction?